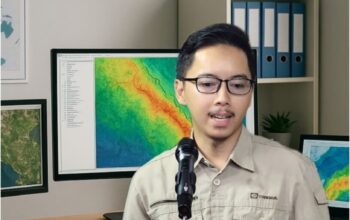Oleh: Andes Robensyah, S.H.,M.H
Dosen Ilmu Hukum UISB & Dirwil LBHA BKPRMI Sumbar
Berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 petanggal 2 Januari 2026 menandai tonggak penting dalam sejarah pembaruan hukum pidana nasional. Untuk pertama kalinya sejak kemerdekaan, Indonesia memiliki KUHP yang sepenuhnya lahir dari rahim bangsa sendiri, menggantikan Wetboek van Strafrecht warisan kolonial. Salah satu terobosan paling progresif dalam KUHP Baru adalah pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) sebagaimana diatur dalam Pasal 2.
Pasal ini membuka ruang bagi hukum adat untuk dijadikan dasar pemidanaan, sepanjang memenuhi syarat tertentu dan diatur dalam Peraturan Daerah (Perda). Secara filosofis dan sosiologis, ketentuan ini mencerminkan penghormatan negara terhadap pluralisme hukum, nilai-nilai lokal, serta keadilan substantif yang hidup di tengah masyarakat. Namun demikian, di balik progresivitas tersebut, terdapat persoalan mendasar yang tidak boleh diabaikan yaitu kekosongan peraturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) sebagai pedoman pembentukan Perda hukum adat.
Masalah ini menjadi semakin mendesak mengingat KUHP Baru telah mulai digunakan. Tanpa kehadiran PP sebagai pedoman nasional, penerapan Pasal 2 KUHP berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, disparitas antar daerah, bahkan pelanggaran hak asasi manusia.
Pasal 2 KUHP Baru merupakan norma yang bersifat terbuka (open norm). Pasal ini mengakui keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat, namun tidak merinci secara teknis bagaimana hukum adat tersebut harus diidentifikasi, dikualifikasi, dibuktikan, dan diterapkan dalam sistem peradilan pidana. Pasal tersebut juga tidak mengatur secara jelas batasan sanksi, mekanisme pengawasan, serta hubungan antara hukum adat dan hukum pidana nasional. Sebagaimana dikatakan oleh Jimly Asshiddiqie bahaw norma terbuka adalah norma undang-undang yang bersifat kerangka (framework law) harus dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan pelaksana agar tidak terjadi kekosongan hukum.
Dalam teori perundang-undangan, norma terbuka harus diikuti oleh peraturan pelaksana agar dapat dijalankan secara efektif dan seragam. Tanpa pedoman teknis, norma terbuka justru berpotensi melahirkan ketidakpastian hukum, yang bertentangan dengan prinsip rechtszekerheid dalam negara hukum.
Pasal 2 KUHP Baru secara eksplisit menyebut Peraturan Daerah sebagai instrumen pengaturan hukum adat. Namun, tidak berarti Perda dapat dibentuk secara langsung tanpa kerangka nasional sebagai pedoman. Dalam sistem hukum Indonesia, Perda adalah peraturan delegasian, yang harus tunduk pada peraturan yang lebih tinggi dan selaras dengan kebijakan nasional. Apalagi, yang diatur adalah pemidanaan, sebuah wilayah hukum yang paling sensitif karena menyangkut pembatasan hak asasi manusia.
Salah satu syarat utama keberlakuan hukum adat dalam Pasal 2 KUHP Baru adalah tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, dan hak asasi manusia. Namun, tanpa pedoman nasional yang jelas, pengujian terhadap syarat-syarat tersebut menjadi sangat subjektif.
Peraturan Pemerintah diperlukan untuk menetapkan standar, seperti kriteria objektif hukum adat yang masih hidup, mekanisme partisipasi masyarakat adat, larangan sanksi yang bersifat merendahkan martabat manusia, prinsip non-diskriminasi dan proporsionalitas dan hubungan antara sanksi adat dan sistem pemidanaan nasional. Tanpa standar tersebut, hukum adat berpotensi disalahgunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan lokal, atau bahkan menjadi sarana diskriminasi terhadap kelompok rentan.
Pedoman tentang hukum adat tersebut tidak hanya dibutuhkan oleh pemerintah daerah, tetapi juga aparat penegak hukum, khususnya hakim. Hakim berada di garis depan dalam menerapkan Pasal 2 KUHP Baru. Tanpa Peraturan Pemerintah sebagai rujukan, hakim akan menghadapi kesulitan dalam menilai: apakah suatu adat benar-benar hidup, apakah Perda tersebut sah secara formil dan materiil, serta apakah sanksi adat sejalan dengan prinsip hukum pidana. Dalam kondisi demikian, sangat mungkin hakim memilih sikap aman dengan tidak menerapkan Pasal 2, sehingga tujuan pengakuan hukum adat dalam KUHP Baru menjadi tidak efektif.
Secara konstitusional, pemerintah memiliki kewajiban untuk menjalankan undang-undang secara efektif. Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan Peraturan Pemerintah guna menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya, begitu juga dalam Pasal 2 ayat (3) KUHP Baru bahwa Peraturan Pemerintah dalam ketentuan ini merupakan pedoman bagi daerah dalam menetapkan hukum yang hidup dalam masyarakat dalam Peraturan Daerah.
Dalam konteks KUHP Baru, Peraturan Pemerintah bukan sekadar pelengkap, melainkan instrumen kunci untuk menjamin implementasi Pasal 2 secara adil dan bertanggung jawab. Menunda pembentukan Peraturan Pemerintah sama artinya dengan membiarkan kekosongan hukum dalam isu yang sangat strategis dan sensitif. Lebih jauh, keterlambatan tersebut dapat menimbulkan ketegangan antara pusat dan daerah, serta membuka ruang bagi uji materiil terhadap Perda yang dibentuk tanpa pedoman yang jelas.